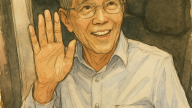Sriwijaya: Jaringan Maritim Nusantara Abad ke-7–13
Pendahuluan
Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kekuatan maritim paling berpengaruh di Asia Tenggara pada abad ke-7 hingga ke-13. Berbasis di wilayah Sumatra bagian selatan (sekitar Palembang modern), Sriwijaya menguasai jalur niaga Selat Melaka dan Selat Sunda, menghubungkan India–Arab–Tiongkok dalam satu jejaring pelayaran yang dinamis. Sumber berita Tiongkok, prasasti Melayu Kuno, hingga temuan arkeologis memberi gambaran tentang bagaimana Sriwijaya memadukan perdagangan, diplomasi, dan agama Buddha untuk membangun hegemoni regional.
Sumber-Sumber Utama: Prasasti dan Catatan Pelancong
Pengetahuan kita tentang Sriwijaya bertumpu pada tiga kelompok bukti. Pertama, prasasti berbahasa Melayu Kuno beraksara Pallawa, seperti Kedukan Bukit (683 M), Talang Tuwo (684 M), dan Kota Kapur (686 M). Kedukan Bukit, yang kini disimpan di Museum Nasional, sering disebut sebagai prasasti tertua berbahasa Melayu Kuno; ia menyinggung perjalanan suci (siddhayatra) oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa sebagai pendiri polity Sriwijaya.
Talang Tuwo mencatat pendirian taman Śrīkṣetra untuk kemakmuran makhluk hidup, menonjolkan etos kesejahteraan dalam pemerintahan awal Sriwijaya. Edisi terbitan Kemdikbud merekam angka tahun 606 Śaka (684 M) serta lokasinya di daerah Bukit Seguntang. Sementara itu, prasasti Kota Kapur di Bangka mencatat ekspedisi militer Sriwijaya serta klaim hegemoninya di kawasan.
Kedua, prasasti Telaga Batu menampilkan daftar jabatan administrasi sekaligus kutukan bagi mereka yang berkhianat, mengisyaratkan kompleksitas birokrasi Sriwijaya sekaligus praktik sumpah setia (sumpah/ritual pengaliran air) yang unik.
Ketiga, catatan biksu Tiongkok Yijing (I-tsing), yang singgah di Sriwijaya pada 671 M saat menuju Nalanda, menggambarkan Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran Buddha Mahayana dan gerbang maritim menuju India. Testimoni Yijing menjadi sumber luar penting tentang peran Sriwijaya di “Maritime Silk Road”.
Lahirnya Sriwijaya: Dapunta Hyang dan “Siddhayatra”
Prasasti Kedukan Bukit menyebut Dapunta Hyang Sri Jayanasa melakukan perjalanan suci (siddhayatra) melalui darat dan air, kemudian “membangun wanua”—yang kerap ditafsirkan sebagai fondasi sebuah permukiman/pusat kekuasaan. Kajian akademik lokal menunjukkan bagaimana narasi “siddhayatra” dipahami sebagai akta pendirian kekuasaan yang berlandaskan karisma dan legitimasi religius.
Dalam rentang 682–686 M, serangkaian prasasti (Palembang, Bangka, Lampung, hingga hulu Batanghari) menandai konsolidasi Sriwijaya di Sumatra bagian selatan dan kontrolnya atas selat-selat strategis. Analisis UNESCO tentang jalur sutra maritim menempatkan Sriwijaya sebagai pengendali choke points dan pengumpul komoditas hutan serta hasil hinterland.
Jaringan Perdagangan, Agama, dan Budaya
Sebagai talasokrasi, Sriwijaya berkembang dari perantara: ia memfasilitasi pelayaran dan pertukaran komoditas (kapur barus, emas, kemenyan, gading, rempah, dan budak), sekaligus menyediakan jasa logistik, perbekalan, perbengkelan kapal, dan perlindungan. Dalam prosesnya, Sriwijaya menyerap dan menyebarkan praktik politik-budaya dari India dan Tiongkok—dari upacara, bahasa administrasi, hingga patronase agama Buddha. Sumber pendidikan populer yang merangkum riset mutakhir menekankan bagaimana Sriwijaya mengadaptasi praktik Tiongkok (tributary trade) dan India (Buddhisme-Nalanda) demi memperkuat legitimasi dan jejaring dagang.
Sebagai pusat studi, Sriwijaya menarik pelajar Asia—termasuk Yijing—dan, pada abad ke-11, biksu Tibet Atīśa disebut tinggal dan belajar di sana sebelum ke Nalanda. Publikasi Kemdikbud menyinggung tradisi intelektual Buddhis tersebut seraya menautkannya dengan ekologi sungai yang menopang kota-pelabuhan.
Struktur Politik dan Administrasi
Dari Telaga Batu, kita menangkap potret birokrasi: rājaputra (pangeran), bhūpati (penguasa daerah), senāpati (panglima), puhāvam (nakhoda), vaniyāga (pedagang), dandanayaka (hakim), sampai pejabat inspeksi kerja (tuhā an vatak). Ragam jabatan ini mencerminkan negara pelabuhan yang terintegrasi dengan ekonomi sungai dan laut—di mana nakhoda, pedagang, dan aparat hukum berada dalam satu skema kontrol pusat. Studi ikonografi juga menyorot tujuh kepala nāga di puncak batu Telaga Batu, mungkin melambangkan proteksi kosmis atas sumpah setia.
Banyak sarjana melihat Sriwijaya sebagai kadatuan (polity berjejaring), dengan inti estuarin di Palembang, hinterland di DAS Musi (sumber komoditas), serta titik-titik muara saingan yang ditekan melalui ekspedisi. Model ini menekankan kontrol atas aliran barang dan alur kapal, bukan okupasi daratan luas.
Hubungan dengan Jawa dan Asia
Relasi Sriwijaya dengan Jawa bersifat fluktuatif—kadang bersahabat melalui kekerabatan dinastik, kadang bermusuhan. Prasasti Nalanda (860 M) menunjukkan Balaputradewa (dengan latar keluarga Śailendra) sebagai dermawan di Nalanda; tradisi ini sering ditafsirkan sebagai jejak elit Jawa yang berkuasa di Sriwijaya pasca konflik di Mataram. Di skala regional, Sriwijaya berinteraksi—bahkan bersaing—dengan Champa, Khmer, dan pusat-pusat Semenanjung Melayu seperti Kedah dan Chaiya.
Pada abad ke-11, peta kekuasaan berubah. Dinasti Chola dari India Selatan melancarkan ekspedisi samudra dan menyerang pusat-pusat Sriwijaya pada 1025 M, memukul tatanan jaringan niaga Asia Tenggara. Narasi ini umum dijadikan tonggak kemunduran Sriwijaya, meski beberapa simpul kekuasaannya tampak bertahan dan beradaptasi.
Kota, Situs, dan Jejak Arkeologis
Palembang kerap ditafsirkan sebagai pusat awal, didukung temuan prasasti serta lanskap sungai-talang yang memungkinkan perahu merayap hingga ke hulu. Jejak Sriwijaya juga bertebaran di Bangka (Kota Kapur), Jambi Hulu (Karang Brahi), dan Lampung (Palas Pasemah). Sementara itu, kompleks candi Muaro Jambi—meski lintas periode dan bercorak Hindu–Buddha—sering dibicarakan dalam diskursus jaringan sungai niaga di Sumatra bagian timur.
Arkeologi sungai menegaskan bahwa kota-pelabuhan estuarin seperti Palembang bekerja sebagai entrepôt (gudang transit), mengumpulkan hasil hutan dan tambang dari hinterland melalui anak sungai (Musi, Batanghari) sebelum dikapalkan ke mancanegara. Model ini menjelaskan mengapa prasasti-prasasti dini tersebar mengikuti rute air, dan mengapa jabatan maritim (nakhoda, pengusaha niaga) menonjol dalam daftar Telaga Batu.
Kemunduran dan Transformasi
Setelah guncangan abad ke-11, kekuatan Sriwijaya tampak terfragmentasi. Persaingan jalur dagang, kebangkitan pusat-pusat baru (sebagian di Jawa), serta perubahan pola permintaan global mengikis posisi monopoli Sriwijaya. Namun, banyak unsur warisannya yang berlanjut: pola kota estuarin yang bertumpu pada sungai, peran perantara dalam jaringan samudra, bahkan kosa-kata administrasi dan hukum maritim. Ringkasan pendidikan populer menempatkan Sriwijaya sebagai contoh awal globalisasi samudra: kerajaan yang lebih mirip jaringan pelabuhan daripada imperium daratan.
Warisan Intelektual dan Linguistik
Penting pula menyorot warisan bahasa. Prasasti Kedukan Bukit tidak hanya penting bagi sejarah politik, tetapi juga linguistik, karena mewakili dokumen awal Melayu Kuno. Kajian-kajian modern kerap menyorot ejaan angka Śaka pada prasasti-prasasti ini, bahkan diskusi filologis tentang bentuk-bentuk angka (termasuk “nol”) yang muncul di Asia Tenggara awal. Walau perdebatan asal-usul “nol” tetap kompleks dan lintas kawasan, topik ini memperkaya pemahaman kita tentang pertemuan budaya dan pengetahuan dalam jaringan Sriwijaya.
Kesimpulan
Gambaran Sriwijaya sebagai talasokrasi Nusantara ditopang oleh bukti epigrafi (Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Kota Kapur, Telaga Batu), catatan pelancong seperti Yijing, serta pembacaan ulang lanskap sungai-estuarin Sumatra. Sriwijaya tidak menaklukkan benua; ia mengikat laut dan sungai—mengelola arus barang, manusia, dan ide. Kejayaannya memperlihatkan bahwa kemakmuran Nusantara sejak awal bertumpu pada kemampuan membaca angin muson, memelihara pelabuhan, dan merawat jejaring kepercayaan antarpedagang lintas samudra. Di tengah tantangan geopolitik abad ke-21, pelajaran Sriwijaya terasa relevan: kekuatan maritim bukan sekadar armada, tetapi juga infrastruktur, tata niaga yang inklusif, dan ekosistem pengetahuan yang tersambung ke dunia.
Daftar Rujukan:
- Kemdikbud RI, Kadatuan Sriwijaya: Perjalanan Suci (PDF)—ringkasan Talang Tuwo dan tradisi Buddhis di Sumatra.
- UNESCO Silk Roads, Trade contacts with the Indonesian archipelago (PDF)—hegemoni Sriwijaya 682–686 M atas selat-selat strategis.
- Telaga Batu Inscription—rincian isi, jabatan administrasi, dan fungsi sumpah.
- Srivijaya—Government & economy—model kadatuan, zona inti-hinterland, serta pelabuhan strategis.
- Khan Academy, The Srivijaya Empire: trade and culture in the Indian Ocean—peran perantara, serangan Chola, dan pertukaran budaya.
- Pranala tambahan: Kedukan Bukit Inscription (profil epigrafi), Kota Kapur Inscription (ekspansi & penertiban), dan kajian lokal tentang tafsir siddhayatra.